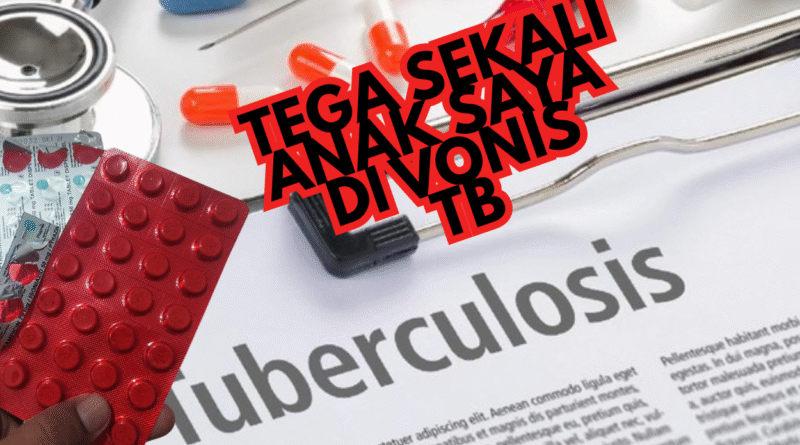Dua Minggu yang Menggetarkan Hati Ketika Vonis TB Hampir Merenggut Senyum Anak Kami
Sebuah benjolan kecil. Hanya sebuah gelembung mungil di bawah leher kanannya yang hanya muncul saat ia bersuara lantang, tertawa lepas, atau berbicara dengan penuh semangat. Seperti sebuah rahasia kecil yang hanya mau diperlihatkan pada momen-momen tertentu. Itulah yang saya dan istri amati pada leher anak pertama kami, seorang bocah lelaki yang sedang aktif aktinya kini sudah duduk di bangku kelas 2 SD.
Rasa penasaran itu adalah tamu yang sudah lama bersarang dalam hati kami. Ia bersemayam sejak ia belum masuk TK, tumbuh perlahan seiring dengan tumbuh kembangnya. Awalnya, kami menganggapnya sebagai hal biasa, sesuatu yang unik dari tubuhnya. Tapi, seperti tetesan air yang terus-menerus melubangi batu, rasa penasaran itu akhirnya berubah menjadi kegelisahan. “Apa ini, ya? Kenapa bisa begitu?” Pertanyaan itu bergaung dalam diamnya ruang hati kami, dari tahun ke tahun.
Akhirnya, saya memutuskan untuk bertindak. Demi fokus, saya mengambil cuti dua hari. Sebuah langkah kecil yang ternyata akan membuka pintu pada sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan gejolak rasa.
Bagian 1: Mencari Jawaban di Balik Rasa Penasaran
Langkah pertama adalah Puskesmas. Dengan hati penuh harap, kami meminta petunjuk. Dokter di sana pun terlihat penasaran. Benjolan itu memang aneh; hanya muncul saat si kecil bersuara keras, menghilang begitu saja dalam kesenyapan, dan sama sekali tidak teraba ketika jari-jari kami menyentuhnya. Seolah ia adalah ilusi. Surat rujukan pun diberikan, dengan enam pilihan rumah sakit. Dengan pertimbangan matang, kami memilih satu. Sebuah pilihan yang kami kira akan segera mengakhiri misteri ini.
Hari Sabtu pun tiba. Suasana rumah sakit begitu familiar dengan kerumunan dan administrasi. Di Poli Anak, setelah menunggu beberapa jam, giliran kami tiba. Ruang pemeriksaan dipenuhi beberapa orang, termasuk seorang dokter muda yang bersemangat. Anak saya diperiksa, beberapa kali disuruh meneriakkan “Aaaa…” dengan keras. Ekspresi dokter yang memeriksa penuh dengan tanda tanya. Akhirnya, keputusan diambil: USG. Sebuah langkah memecahkan kegelisahan, pikir kami.
Sebelum ke radiologi, seorang perawat berbisik lembut, “Pak, dokter poli anak hanya sampai jam 11. Kalau bisa, bawa hasil USG-nya besok Senin pagi, ya.” Saya mengangguk patuh, “Nggih, Mbak.” Antrian di radiologi ternyata sangat panjang. Ruang tunggu dipenuhi oleh wajah-wajah yang memendam cerita dan kecemasannya masing-masing. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya giliran anak saya tiba.
Proses USG berlangsung. Si kecil dengan patuh mengikuti perintah dokter untuk meneriak dan diam. Saya memperhatikan layar monitor penuh konsentrasi, meski tak mengerti apa-apa. Setelah selesai, dokter USG berkata, “Saya melihat kayak ada pelebaran pembuluh darah.” Lalu, sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi sangat berarti, “Anaknya pernah diberi suntikan antibiotik ke bagian bawah kulit nggak?” Saya, yang kaget dan bingung, hanya bisa menjawab, “Lupa, Dok.” Dokter itu kemudian menyerahkan sepenuhnya pada dokter poli untuk penjelasan detail. Kami keluar, menunggu hasil cetakan selama 30 menit yang terasa seperti 3 jam. Dengan selembar kertas hasil USG di tangan, kami pulang, membawa serta bayangan “pelebaran pembuluh darah” dan pertanyaan tentang suntikan antibiotik.
Bagian 2: Vonis yang Menghantam Bagai Petir di Siang Bolong
Hari Senin. Saya datang pagi-pagi buta, nomor antrian 8. Kali ini, saya sendirian. Pikiran praktis berkata, “Ini hanya urusan ambil hasil dan konsultasi, tak perlu ganggu sekolah si kecil yang sedang ujian.” Sebuah keputusan yang ternyata keliru.
Saya masuk ke ruang pemeriksaan. Dokternya berbeda. Bukan dokter yang memeriksa hari Sabtu lalu. Dokter ini langsung membaca hasil USG sambil bertanya, “Mana anaknya?”
“Di sekolah, Dok.”
“Kalau bisa, hari ini anaknya dites darah lengkap, ya. Bisa kan dibawa?”
“Oh, bisa, Dok.”
Selembar kertas pengantar lab diberikan. Mata saya menyapu cepat tulisan di sana: Pemeriksaan Darah Lengkap. Dan di bawahnya, ada satu baris ceklist yang membuat jantung saya berhenti sejenak: Tes HIV.
HIV? Kenapa? Pertanyaan itu melintas cepat, tapi saya tepis. Mungkin ini prosedur standar. Saya segera menjemput si kecil dari sekolah, membawanya ke lab dengan hati sedikit cemas. Dua tabung darah kecil diambil dari lengan mungilnya. Hasilnya harus diambil 2 jam setelah uji. Sepanjang hari, rasa cemas mulai merayap, tetapi saya berusaha menenangkan diri.
Hari Selasa. Kali ini, saya membawa serta si kecil. “Siapa tau ada tes lagi,” pikir saya. Sebelum dipanggil, saya bertanya pada perawat, “Bu, kenapa tiap hari beda-beda dokternya?”
“Oh iya, Pak. Memang berganti-ganti, karena banyak dokter anaknya.”
Saya sedikit kecewa. Saya berharap bisa bertemu dokter yang sama untuk konsistensi. Giliran kami tiba. Kami masuk. Dokternya berbeda lagi. Bukan dokter Sabtu, bukan juga dokter Senin. Dokter ketiga ini menerima hasil lab, berbisik sesuatu dengan perawat yang tak saya pahami. Lalu, dengan tenangnya, ia berkata:
“Pak, anak Bapak kena TB Kelenjar.”
Dunia seketika runtuh. Kata-kata itu menggema di telinga saya, keras dan menusuk. TB Kelenjar. Sebuah nama penyakit yang selama ini hanya saya dengar dari cerita, dari berita, tiba-tiba hinggap di tubuh mungil anak saya. Saya langsung lemas. Seketika, bayangan tentang perjuangan panjang, obat-obatan, dan stigma sosial menghantui pikiran.
Saya mencoba bertaya, “Dok, beneran TB? Kami cuma mau tau soal benjolan di lehernya.”
“Iya, Pak. Hasil USG menunjukkan ada benjolan.”
Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang begitu teguh, seolah semuanya sudah pasti. Dalam hati, saya bergumam, Bismillah… Inilah takdir Allah. Apapun yang terjadi, ini sudah kehendak-Nya. Sebuah upaya untuk menenangkan diri yang hampir mustahil dilakukan.
Resep obat diberikan. Penjelasan singkat tentang disiplin minum antibiotik selama 6 bulan. Kami diarahkan ke apotek. Di sana, seorang apoteker yang sangat telaten memberikan penjelasan panjang lebar. Ia bahkan bertanya pada si kecil tentang sekolah dan hafalan Qur’annya. “Pak, qadarullah ya,” katanya dengan lembut. “Si kecil kena TB. Bapak harus ikhlas dan disiplin dalam memberikan obatnya. Kita coba dulu 15 hari, 4 tablet perhari. Minumnya jam 5 pagi, setelah sholat Subuh.”
Pulang dari rumah sakit, motor yang saya kendarai terasa seperti ruang hampa. Saya belum bisa menerima vonis ini. Pikiran dan perasaan berontak. Ini tidak benar. Anak saya sehat. Ia tidak batuk-batuk, tidak lesu, energinya melimpah ruah, selalu ceria. Satu-satunya “kelainan” adalah berat badannya yang kurang 2 kg dari ideal. Apakah itu cukup untuk menjatuhkan vonis seberat ini?
Bagian 3: Keraguan dan Percikan Harapan dari Sebuah Percakapan
Malam itu, saya hampir menangis. Membayangkan perjuangan yang harus dijalani anak saya, beban yang harus ia tanggung di usianya yang masih begitu belia. Saya dan istri saling memandang, sama-sama melihat keraguan di mata masing-masing. Kami belum menerima. Keyakinan kami sebagai orang tua berkata: Ada yang tidak beres.
Kami sepakat untuk tetap memulai pengobatan esok harinya, Rabu. Alarm disetel jam 5 pagi. Kami ingat betul pesan apoteker: telat beberapa jam saja, perjalanan pengobatan bisa harus diulang dari awal. Dengan berat hati, kami memulai ritual pagi itu, membujuknya menelan empat butir tablet yang bagi kami adalah simbol vonis yang tak kami yakini.
Dua hari berlalu. Obat tetap diminum, tapi keraguan tak juga hilang. Malah, semakin menjadi. Saya iseng mencari informasi di internet, membrowsing ciri-ciri TB Kelenjar. Saya tidak menemukan satu pun yang cocok dengan kondisi anak saya. Benjolan pada TB Kelenjar biasanya jelas, teraba, dan menetap. Bukan hilang-timbul seperti miliknya.
Di kantor, saya bercerita pada seorang rekan tentang kronologi ini. Ia langsung menyergap, “Udah dites Mantoux belum?”
“Mantoux? Apa itu?”
“Itu tes suntik di bawah permukaan kulit. Kalau benar TB, akan muncul warna merah diikuti benjolan.”
Ohhhh! Seketika itu juga, puzzle mulai tersusun. Itulah makna pertanyaan dokter USG waktu itu! “Anaknya pernah diberi suntikan antibiotik ke bagian bawah kulit nggak?” Itu adalah deskripsi yang keliru untuk tes Mantoux! Dokter USG itu mungkin sedang mencarinya di rekam medis, tapi karena saya lupa, ia tak meneruskannya.
Lalu, rekan lain ikut nimbrung, “Pak, dulu saya juga divonis kelenjar dan disuruh operasi. Kakak saya tidak yakin, cari second opinion, dan ternyata benar, bukan itu penyakitnya.”
Percakapan singkat itu seperti membuka tabi. Sebuah percikan harapan. Saya segera minta rekomendasi dokter anak yang terpercaya. Jaringannya bekerja. Seorang teman yang memiliki kenalan di rumah sakit yang sama meminta nomor rekam medis anak saya.
Dan inilah kejutan lainnya: setelah dicek, ternyata anak saya pernah melakukan tes Mantoux dan Rontgen paru pada Desember 2024! Saya benar-benar lupa. Dan hasilnya? Negatif.
Saya seperti tersiram air dingin. Negatif? Tapi kenapa divonis TB? Teman yang di RS itu pun bingung. “Mungkin dokter menafsirkan hasil Mantoux dan Rontgen lama itu sudah tidak berlaku,” katanya. Tapi naluri saya berkata lain. Seharusnya, tes itu diulang sebelum vonis dijatuhkan. Sarannya tegas: “Coba periksa ke tempat lain.”
Saya menelepon istri, menceritakan semua penemuan baru ini. Suaranya di seberang telepon terdengar lega, sekaligus marah. Ternyata, ia juga sudah berkonsultasi dengan dokter langganannya dan mendapat saran yang sama: cari second opinion.
Bagian 4: Kebenaran di Ujung Perjalanan: Sebuah Pembuktian
Hari itu juga, kami memutuskan untuk membawa si kecil ke rumah sakit lain, yang direkomendasikan dokter langganan istri. Sebuah ironi yang luar biasa terjadi. Dokter yang memeriksa di RS baru ini ternyata adalah dokter yang pertama kali memeriksa anak saya pada hari Sabtu lalu! Dokter yang penasaran dan meminta USG itu.
Wajahnya terlihat familiar. Kami pun bercerita panjang lebar, mengurai seluruh kronologi, termasuk vonis TB dan obat yang sudah 2 hari diminum. Wajah dokter itu berubah serius. Ia memeriksa leher si kecil sekali lagi.
“Saya baru kali ini lihat kasus benjolan di leher seperti ini,” katanya. “Kalau TB Kelenjar, biasanya terlihat langsung, dan kalau dirabakan, terasa banget benjolannya. Ini tidak.” Lalu ia bertanya, “Kemarin sudah dites Mantoux?”
“Belum, Dok.”
“Lhooo… seharusnya di-Mantoux dulu. Saya waktu itu minta USG karena penasaran dengan bentuk benjolannya, bukan untuk mendiagnosa TB.”
Kata-katanya seperti membebaskan kami dari belenggu. Seharusnya di-Mantoux dulu. Kalimat sederhana yang menjadi kunci segalanya. Ia lalu menjadwalkan tes Mantoux untuk esok harinya.
Keesokan harinya, si kecil menjalani tes Mantoux. Sebuah suntikan kecil di lengan. Kami harus menunggu 72 jam untuk membacanya. Kami diarahkan untuk kembali pada hari Senin. Tapi, trauma akan berganti-ganti dokter masih membekas.
“Saya tidak mau kejadian seperti di awal, Bu,” kata saya pada perawat. “Hari Senin nanti, siapa dokternya?”
“Dokter A.”
“Kok bukan dokter yang sekarang? Gimana nanti, bisa beda vonis lagi.”
Dokter yang memerintahkan Mantoux itu pun menenangkan, “Tidak apa. Dokter A . Kalau cuma baca hasil Mantoux, tidak masalah.” Kami pun menurut, meski dengan sisa was-was.
Hari Senin yang menegangkan pun tiba. Kami bertemu dengan Dokter A. Dan benar, ia sangat berbeda dengan dokter yang menjatuhkan vonis. Ia ramah, mendetail, dan penuh perhatian. Lama kami berdiskusi. Penjelasannya sangat masuk akal dan sejalan dengan dokter pertama (yang memerintahkan Mantoux).
Akhirnya, setelah memeriksa bekas suntikan di lengan si kecil yang sama sekali tidak menunjukkan reaksi signifikan, ia berkata dengan senyum melegakan, “Hasil Mantoux-nya negatif. Anak Bapak tidak terkena TB Kelenjar.”
Negatif.
Kata itu terdengar seperti menenangkan. Tidak terkena TB Kelenjar.
Qadarullah, memang. Takdir Allah berbicara dengan caranya yang misterius. Obat yang sudah diminum selama 2 hari? Kata dokter, tidak apa-apa, tidak membahayakan. Alhamdulillah ‘ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.
Sebuah Renungan dari Dua Minggu yang Penuh Warna
Perjalanan hampir dua minggu ini adalah roller coaster emosi yang dahsyat. Dari rasa penasaran, harapan, kecemasan, hingga kehancuran akibat vonis yang tergesa-gesa, lalu diakhiri dengan kelegaan yang tak terkira. Ini adalah pelajaran berharga bagi kami sebagai orang tua.
Kami belajar bahwa seorang orang tua adalah advokat terbaik bagi anaknya. Naluri kami, yang sejak awal meragukan vonis itu, ternyata benar. Jangan pernah ragu untuk bertanya, untuk meminta penjelasan, dan terutama, untuk mencari second opinion ketika hati terasa tidak nyaman. Kesehatan anak adalah taruhannya.
Kami juga belajar tentang betapa rapuhnya sistem yang seharusnya menjadi tempat kita berharap. Berganti-ganti dokter tanpa komunikasi yang baik, vonis yang dijatuhkan tanpa pemeriksaan penunjang yang lengkap (Mantoux), dan ketergesaan dalam memberikan obat yang memiliki efek samping jangka panjang, adalah cacat dalam sistem yang harus diperbaiki. Sebagai pasien, kita harus kritis dan pro-aktif.
Dan yang terpenting, kami belajar tentang sabar dan tawakal. Kami berusaha menerima vonis awal dengan ikhlas, seraya terus berusaha mencari kepastian. Keyakinan kami bahwa “ini sudah takdir” bukanlah bentuk pasrah buta, tapi justru menjadi kekuatan untuk melalui badai sambil terus berikhtiar.
Benjolan di leher si kecil? Ternyata, menurut dokter terakhir, itu hanyalah sebuah anatomi pembuluh darah yang sedikit menonjol saat ia mengejan atau bersuara keras. Bukan penyakit. Bukan ancaman. Hanya sebuah keunikan dalam tubuh mungilnya yang penuh keajaiban.
Malam ini, alarm jam 5 pagi tidak lagi berbunyi untuk mengingatkan obat pahit. Ia berbunyi untuk mengingatkan kami akan sholat Subuh, untuk bersyukur atas nikmat kesehatan yang hampir saja “dicuri” oleh sebuah diagnosis yang keliru. Senyum ceria si kecil, tawanya yang menggelegar, dan lompatannya yang penuh energi, kini memiliki makna yang jauh lebih dalam.
Ini adalah cerita kami. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap label dan vonis, ada seorang anak dengan masa depannya, dan ada orang tua yang akan terus berjuang, bertanya, dan tidak pernah menyerah untuk mendapatkan yang terbaik bagi buah hatinya. Karena cinta seorang orang tua, pada akhirnya, adalah obat yang paling mujarab. [SR]